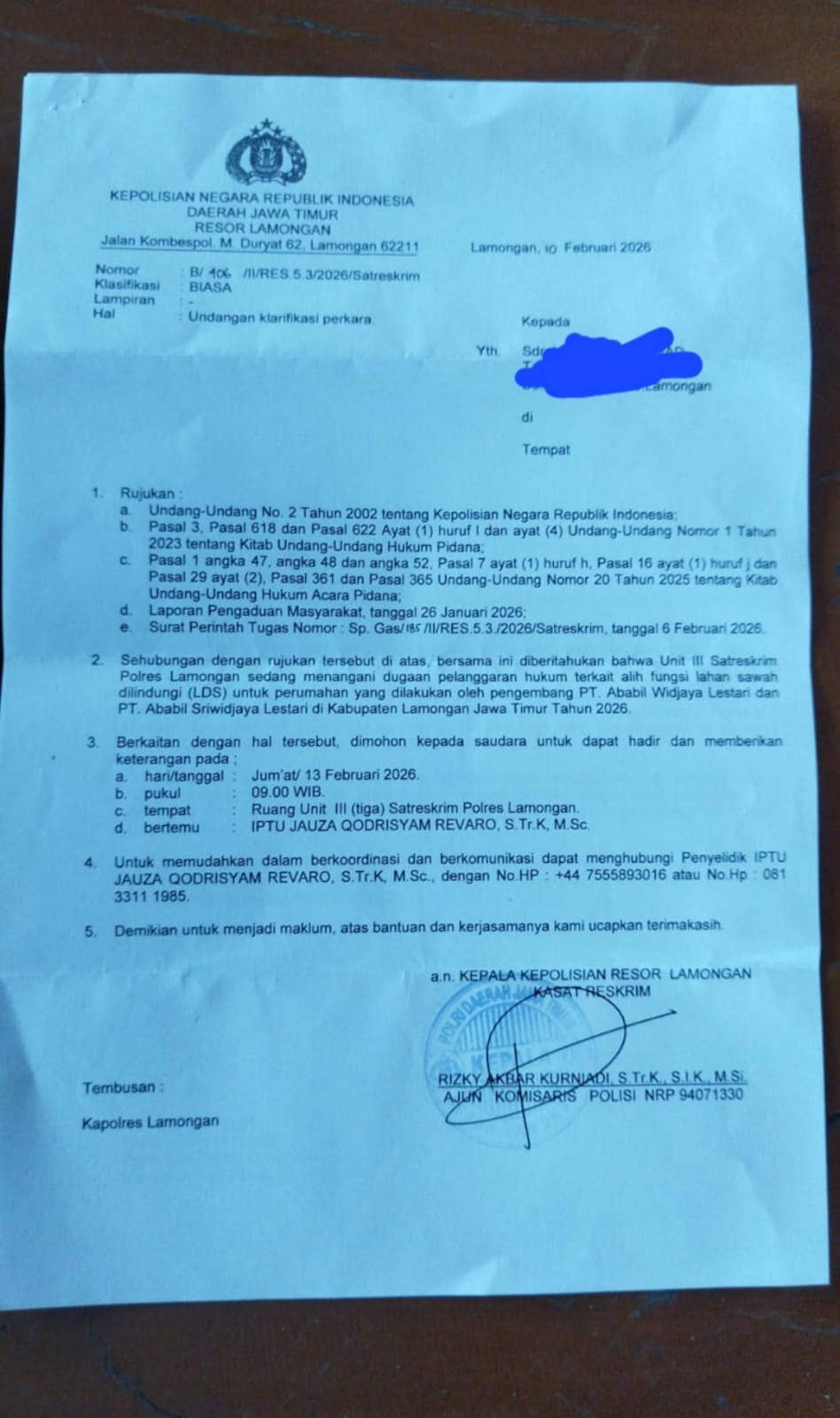Pendawa || Wacana pengembalian pemilihan kepala daerah kepada DPRD adalah salah satu gagasan paling mundur dalam konsolidasi demokrasi lokal pasca reformasi. Argumen bahwa Pilkada langsung mahal hanyalah alasan estetis untuk menutupi upaya mengembalikan ruang politik ke meja-meja elit yang jauh dari pengawasan rakyat.
Saya jauh lebih percaya bahwa masalah demokrasi kita bukan terletak pada siapa yang memilih kepala daerah, tetapi siapa yang mengendalikan proses politiknya. Dan disinilah Pilkada langsung masih menjadi satu-satunya kanal yang memberi rakyat hak menentukan arah pemerintahan daerah tanpa perantara elit.
*Regulasi Jelas, Motif yang Tidak Jelas*
Pilkada langsung memiliki fondasi regulatif yang kuat melalui UU No. 10 Tahun 2016 dan berakar pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menegaskan kepala daerah dipilih secara demokratis. Kata demokratis tidak pernah ditafsirkan sebagai “dipilih oleh DPRD” kecuali pada masa transisi awal reformasi, ketika negara belum memiliki kapasitas institusional untuk menggelar pemilu langsung di daerah.
Hari ini negara punya kapasitas itu. Bahkan Pilkada serentak telah berjalan sejak 2015. Pertanyaannya: kenapa justru sekarang ada dorongan untuk kembali ke belakang?
Tidak ada jawaban yang rasional kecuali motif pengendalian politik. Ketika proses pemilihan kembali ke DPRD, bargaining untuk memilih kepala daerah hanya membutuhkan ruang sempit: cukup memenangkan 25-50 suara anggota DPRD, bukan ratusan ribu suara rakyat.
Itulah pintu masuk oligarki paling efisien.
*Biaya Tinggi? Demokrasi Memang Tidak Pernah Murah*
Mereka yang menganggap Pilkada langsung terlalu mahal sering kali sengaja lupa bahwa otoritarianisme jauh lebih murah, karena tidak butuh kotak suara, panitia pemilu, logistik, dan pengawasan. Tapi apakah itu lebih baik? Jelas tidak.
Negara demokratis tidak boleh berlogika efisiensi dalam memilih pemimpin. Kalau alasannya biaya, maka solusi teknisnya ada, mulai dari:
memperbaiki pembiayaan partai
memperkuat audit dana kampanye,
memperketat larangan money politics
memotong jeda kampanye
digitalisasi tahapan pemilu.
Tetapi yang ingin instan akan memilih satu solusi pendek: cabut saja hak pilih rakyat.
*Risiko Politik Lebih Besar di DPRD*
Model Pilkada melalui DPRD akan menciptakan utang politik struktural kepala daerah kepada anggota DPRD. Siapapun yang dipilih akan memulai masa jabatan dengan daftar tagihan: jabatan, proyek, anggaran, dan kebijakan.
Check and balance langsung runtuh. Karena bagaimana mungkin DPRD mengawasi kepala daerah yang mereka pilih sendiri? Ini ibarat makelar yang mengawasi klien yang baru saja membeli barang dari dirinya.
*Otonomi Daerah Tanpa Rakyat? Mustahil*
Desentralisasi politik dalam UU 23/2014 bukan hanya soal distribusi anggaran, tetapi juga distribusi kedaulatan. Jika kepala daerah kembali dipilih DPRD, otonomi daerah hanya menyisakan struktur tanpa rakyat.
*Otonomi tanpa rakyat adalah imitasi demokrasi.*
Kesimpulannya, Mengembalikan Pilkada ke DPRD bukan upaya perbaikan sistem pemilu, tetapi upaya resentralisasi kekuasaan di tangan elit politik. Dan setiap kali hak rakyat dirampas dengan alasan efisiensi dan biaya, itu selalu pertanda bahwa demokrasi sedang disabotase dari dalam.
Bagi saya, rakyat tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan dan konsumen kebijakan, tetapi juga pemilik mandat. Karena mandat tanpa hak pilih hanyalah penipuan konstitusional.
Dan kita sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke masa ketika pemimpin cukup ditentukan di ruang tertutup oleh segelintir orang.
_Oleh: Haryono (Kang Har), Ketua LSM Suara Malowopati Bojonegoro & Pengamat Kebijakan Publik_(hl)